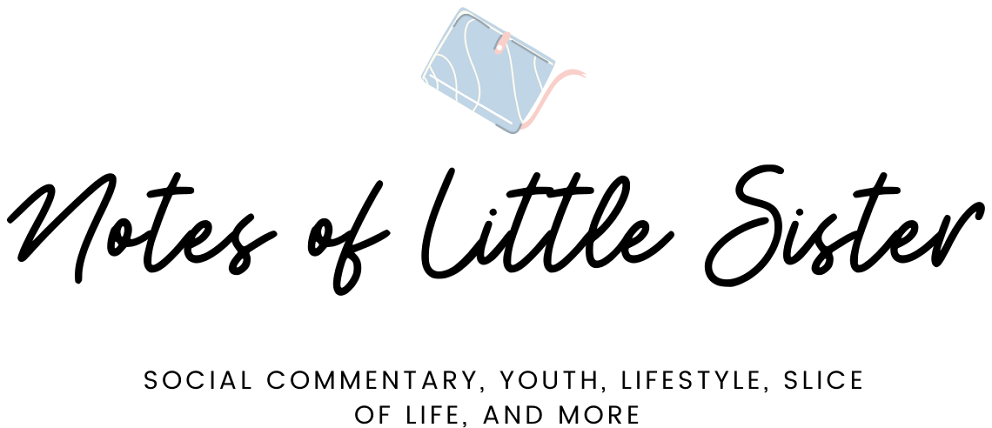Ada yang menarik dari bagaimana orang-orang saat ini menunjukan karakternya satu sama lain di media sosial. Setiap kali ada opini, perdebatan atau hal-hal yang bertentangan dari mayoritas, maka dianggap menyimpang, sesat dan perlu diluruskan. Bukan hanya hal-hal yang menyangkut ideologi atau keyakinan, tapi juga tentang preferensi, prinsip dan nilai-nilai kehidupan itu sendiri yang pada dasarnya tentu sangatlah personal.
Daripada menyampaikan argumen dengan baik, seringkali kita merasa paling benar ketika berdiskusi atau beradu pendapat dengan seseorang. Sehingga saat menjumpai hal yang bergeser dari apa yang kita percayai, seolah ada kecenderungan untuk selalu mau mengoreksi persepsi lawan agar bisa sesuai dengan milik kita. Padahal, sikap seperti ini pada akhirnya bisa berujung menyakiti orang lain, bahkan diri kita sendiri.
Alih-alih membuka diskusi dengan nyaman, akhir-akhir ini gue sering melihat bagaimana kebanyakan orang di internet justru lebih senang pointing out their logical fallacy terhadap kubu yang "terlihat berbeda" dan memposisikan mereka di kotak yang salah, seakan-akan pemikiran dan pengalaman mereka nggak sama validnya untuk di bawa ke permukaan, seakan-akan ada kamus benar dan salah dalam menyampaikan gagasan.
Gue nggak bisa menemukan penyebab mengapa orang-orang ini bisa secara lantang menyerang individu lain dengan alasan defending their beliefs, selain keegoisan yang selalu butuh untuk diberi makan. Bahkan sesederhana perkara bubur diaduk atau nggak, we can also be easily offended as if there has to be the right way to eat porridge.
Kondisi ini membuat gue terasa relate ketika membaca bab favorit dari buku The Things You Can See Only When You Slow Down tentang "menjadi benar" karya Haemin Sunim. Menurut beliau, menjadi benar itu nggak sama pentingnya dengan saling memberi rasa nyaman dan bahagia, karena setiap orang sebetulnya punya keyakinan, nilai-nilai dan pemikiran mereka sendiri yang pasti sangat fundamental untuk mereka that we cannot imagine compromising on. Trying to convince someone to adopt our views is largely the work of our ego. Even if we turn out to be right, our ego knows no satsfaction and seeks a new argument to engage in.
Ini yang bikin gue sering takut dan malas akhir-akhir ini ketika mengemukakan pendapat di media sosial, terlebih lagi Twitter (walaupun cuma nge-tweet alakadarnya dan bukan beropini). Gue sering ditampakan dengan orang-orang yang hobi saling serang satu sama lain hanya untuk memperjuangkan apa yang menurutnya benar. Lebih parah lagi, they did it on purpose, semata-mata untuk mendapatkan pleasure atau kepuasan sendiri atas argumen kosong yang dilontarkan.
Well, nggak ada salahnya mempertahankan persepsi dan value kita. Tapi ketika sudah memperlakukan lawan bicara selayaknya musuh yang nggak punya thinking process, itu justru akan membuat diskusi jauh dari kata nyaman. What's the point of discussion kalau ujung-ujungnya memaksa orang lain untuk punya value yang sama? Bahkan di dalam agama gue sendiri, dakwah yang baik adalah dakwah yang dilakukan dengan respectful, bukan dengan kekerasan, baik berupa verbal atau fisik.
Bukankah setiap orang punya pendapat dan pengalaman yang berbeda? Pengalaman gue nggak mungkin exact sama dengan pengalaman orang lain, bahkan teman-teman gue. Apa yang mendasari mereka untuk punya pendapat atau sudut pandang yang berbeda juga nggak mesti harus sama. Begitu juga dengan prinsip dan proses pendewasaan gue, bisa berbeda tergantung bagaimana gue tumbuh. Awl yang sekarang, bukan Awl yang sama dengan lima tahun lalu. Dan gue nggak berharap gue yang sekarang adalah orang yang sama beberapa tahun berikutnya. I want to be a better person.
Maka dari itu, sekarang gue lebih senang melipir di pojokan setiap kali melihat keributan di internet. Gue hanya senang memikirkannya sesaat sampai lupa begitu aja, tanpa gue "dokumentasikan" seperti biasanya disini. Terkadang memang ada banyak hal yang baiknya di-yaudahin dan didiemin aja, walaupun nggak salah juga kalau kita mau menuliskan itu dan membagikannya ke orang lain.
Mungkin sisi positifnya gue jadi bisa lebih kalem dan objektif sebelum menyimpulkan sesuatu, tapi sisi negatifnya gue jadi takut untuk bersuara dan menggali potensi gue lebih jauh lagi. Apakah ini wajar? Bahkan sampai pada titik dimana setiap kali dapat notifikasi, gue langsung merasa gelisah sebelum ngecek notifikasi itu. Gue langsung overthinking, apakah ada omongan gue yang salah? Apakah gue salah nge-tweet atau nulis komentar? While I didn't even tweet something, yet the problem is on them and not me.
Dari sini gue jadi belajar, betapa ucapan seseorang itu bisa memberi pengaruh yang signifikan terhadap psikis orang lain. Now that I have learned something, baik sebagai orang yang dipojokan dan memojokan (I'm not gonna lie that I've also behaved like one at least once in my life or even more), gue akan lebih menjaga kata-kata gue setiap kali menyampaikan sesuatu, even untuk hal yang menurut gue benar dan perlu diluruskan. Because I don't know what they've been through that makes them bring things to the table.