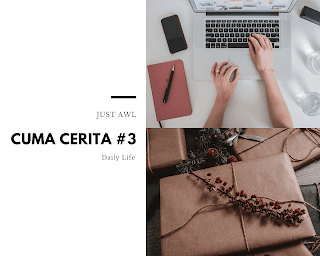Pernah nggak sih lo ngalamin keserimpet atau ketubruk-tubruk pas lagi jalan di suatu tempat yang padatnya bukan main? Gue sering, dan saking seringnya, gue selalu nggak betah berjalan lama-lama atau secara lamban di ruang publik.
Mungkin karena kebiasaan gue yang selalu ingin cepat dan nggak suka berlambat-lambat ria ketika berada di ruang publik, baik itu di trotoar, mall, jalan lebar, pasar, dsb.nya, jadi gue selalu nggak betah kalau berada di sana lama-lama dan selalu nggak sabar untuk mendahului. Ingin langsung syung syung syunggg gitu. Ini serius. Sampai-sampai sambil berjalan gue suka heran dan mikir sendiri, ini orang-orang yang lelet emang jalannya santai atau mereka lagi banyak pikiran jadi jalan sambil melamun? Ataukah mereka simply memang nggak peduli kalau jalannya terlalu ke tengah dan menghalangi jalanan orang lain? Sambil ngobrol cekakak cekikik pula? Saking cepatnya, pernah ketika gue lagi jalan sama tante gue, beliau ketinggalan jauh di belakang dan gue dibilang kayak orang Jepang karena cara jalannya yang nggak santai. Jiaah, kuliah bahasa Jepun bukan berarti jadi orang Jepun juga bund😆
"Emangnya mau kemana sih, neng, buru-buru amat!"
"Mau pulang lah, pak. Demen kalik saya lama-lama di jalanan😫."
Sebetulnya bisaa sih, santai, rileks, nggak perlu buru-buru. Namun hal itu hanya bisa dilakukan saat gue ingin menikmati momen-momen tertentu, misalnya saat lagi jalan pada Minggu pagi di kampus atau di CFD, dan saat mau pilih-pilih baju atau buku di toko—itupun sambil merhatiin situasi di sekeliling gue, apakah lagi ramai sentosa atau nggak. Kalau lagi ramai ya mending balik aja guehh😰. Suwer, berada di kerumunan lama-lama bikin sakit kepala. Gue susah fokus!
Setelah beberapa bulan ini merasakan, tinggal di kota kecil nyatanya nggak jauh berbeda dengan kota-kota besar yang macetnya terkenal bukan main. Apalagi pada jam-jam istirahat dan pulang kerja. Dan di masa-masa mendekati lebaran kayak gini, nih, justru menurut gue macet dan riweuhnya lebih parah daripada ketika gue masih di Bandung bulan puasa tahun-tahun sebelumnya. Berarti kebayang, kan, semacet apa? Kalau sebelumnya gue lebih sering kesal sama lampu merah yang lamanya bikin males dan pusing, justru sekarang gue lebih sering kesal sama perilaku manusia-manusianya. Dahlah jalanan nggak lebar, trotoar sempit, angkutan umum bertebaran dari yang sebelah jalan paling pinggir sampai yang paling tengah sekalipun, banyak pula orang-orang yang malah berdiam diri atau mengobrol ria di trotoar yang sudah sempit itu, ditambah prokes dilakukan alakadarnya karena nggak semua orang masih aware dengan covid-19 yang belum usai ini.
"Lah terus, ente sendiri ngapain ikut-ikutan ngeramein jalanan?"
Kebetulan ada beberapa barang yang harus gue beli, dan sejujurnya gue sendiri jarang keluar kemana-mana karena males, terbukti dengan udara panas dan macet yang nggak karuan bikin makin enggan untuk keluar.
Nggak terhitung berapa kali rasanya gue ingin teriak dan punya kekuatan super yang bikin orang-orang ini jadi langsung tertib. Wushh! Tapi, siapa gue?
Lambat laun, sambil merasakan badan yang dicolek ibu-ibu dari belakang karena beliau tampaknya buru-buru juga (saya pun sama buu, bentar ya, sabar ya buu, orang depanku ini lama kalik bu😭), gue belajar bahwa ternyata our responses are all matters.
Beberapa kali gue agak menyahut tak sabar saat orang di belakang gue menuntut untuk lebih cepat, sementara jalanan di depan fully tertutup dan nggak bisa ditembus lagi oleh orang yang memang selalu ingin cepat seperti gue. Beberapa kali juga gue terpaksa menerobos supaya orang yang menghalangi jalan itu sadar bahwa mereka berdiri terlalu ke tengah dan mengganggu kenyamanan orang lain. Semua respon atas situasi tidak menyenangkan itu gue tanggapi selalu dengan emosi, dengan ego yang memaksa untuk nggak mau jalan berlama-lama. Gue nggak memberikan ruang untuk kepala gue bersikap lebih dingin dan melihat dari sisi positif.
Padahal, di depan gue ada anak perempuan dan ibunya yang lagi semangat ngobrolin soal baju model apa yang mau mereka beli—mungkin hari raya jadi momen langka untuk mereka bisa punya baju baru. Nggak jauh dari sana, ada pasangan suami istri dan anaknya yang masih kecil yang tampak sesak kepanasan dan kebingungan untuk menentukan, akan ke arah mana lagi mereka pergi, ditambah barang belanjaan di kanan kiri mereka. Di depan gue juga ada banyak sekali tukang dagang yang hopeless menawarkan dagangan mereka untuk pejalan kaki yang abai begitu aja.
Di antara mereka ada tukang sandal, tukang peci/kopiah, tukang mainan, tukang celana, tukang cilok, tukang rujak, sampai pedagang asongan yang giat nawarin minuman ke anak kecil dan mbak-mbak yang mungkin saja lagi nggak shaum. Gimana kalau dagangan mereka terinjak-injak atau terjatuh karena gue yang serabat serobot dan egois ingin cepat-cepat terbebas dari hiruk pikuk? Belum lagi ada nenek-nenek yang jalan sambil bawa kantong kresek di tangannya, dan anak kecil yang lagi jongkok sambil nangis menunggu mamanya karena mungkin juga sudah gerah ingin cepat pulang. Gimana kalau kepala anak kecil ini kesenggol sama kantong belanja gue yang lumayan berat hanya karena gue ingin buru-buru dan nggak ngeh dengan kehadirannya yang kurus dan kecil itu?
Sebagaimana hidup kita yang nggak lepas dari lalu lalang orang melintas, ada kalanya kita nggak bisa melawan hal-hal yang memang berada di luar kontrol kita. In this case, gue memaksa ingin cepat, menegur orang dengan cara nggak baik seolah-olah terlihat gue memikirkan juga kondisi orang di belakang gue padahal kenyataannya gue hanya mementingkan urusan gue sendiri, sementara perihal kecepatan berjalan atau cara orang berjalan dan kesadaran mereka tentang situasi sekitar bagaimanapun adalah sesuatu yang nggak bisa gue kontrol. Sekalipun bisa, mungkin hanya berlaku untuk satu atau dua orang yang gue tegur tadi. Selebihnya, gue bukan polisi, bukan security atau petugas dishub yang punya wewenang untuk mengatur keadaan disana. Itulah kenapa, respon gue menjadi segalanya. Karena satu-satunya orang yang bisa gue kontrol adalah diri gue sendiri, pola pikir gue.
Detik itu juga gue berusaha mengubah respon gue dengan senyuman. Walaupun senyum gue mungkin nggak terlihat karena tertutup masker, paling tidak senyuman itu berguna untuk bisa menenangkan diri sendiri. Menyiram api-api yang sedari tadi nggak berhenti menyala di kepala gue. Awalnya susah memang, apalagi kalau situasi nggak menyenangkan itu masih berlangsung gue rasakan. Bahkan pada respon berikutnya gue hampir menggerutu lagi, tapi sesaat kemudian gue harus mengingatkan diri sendiri untuk bersabar. Toh pada akhirnya gue hanya bisa maklum. Karena gue bukan sedang berada di Shibuya crossing yang meskipun tempat penyeberangan disana merupakan yang paling sibuk di dunia, semua pejalan kaki yang melintas patuh pada aturan. Gue juga bukan sedang berada di Jerman yang memang terkenal sebagai negara ramah pejalan kaki dengan infrastruktur yang baik. Bukan pula sedang berada di Korea Selatan yang termasuk negara dengan mobilitas tinggi, tanpa harus menyaksikan mobil-mobil dan angkutan umum chaos di sisi jalan. Gue hanyalah anak manusia yang berada di belahan dunia lain di Indonesia, yang kondisinya jauh sekali dari apa yang gue sebutkan di atas. Maka yang bisa gue lakukan adalah bersabar, dan maklum.
"Tapi apa itu artinya sah-sah aja kalau seseorang menghalangi jalanan bagi pejalan kaki yang lain?"
Bagi gue sendiri, punya rasa peka dan kepedulian yang tinggi, serta nggak menjadi ignorant saat lo sedang berada di public place semacam trotoar, mal, dsb.nya adalah sesuatu yang penting. Meski kenyataannya sulit, gue sendiri masih berusaha untuk nggak semata-mata memikirkan diri sendiri saat berada di jalan. Barangkali, kan, ada orang yang membutuhkan bantuan gue saat di tengah perjalanan itu. Gue maklum nggak semua orang punya awareness ini, tapi gue juga berharap bahwa kita bisa lebih tertib lagi ketika berbaur atau bersosialisasi dengan orang lain di ruang terbuka. Karena nggak semua orang bisa santai di jalan, nggak semua orang juga jalan-jalan untuk berlibur dan beli baju. Ada kok, yang semata-mata keluar hanya untuk beli bahan makanan buat buka puasa.
Tulisan kali ini gue dedikasikan sesuai dengan tema "Jalan" untuk awal bulan dari #1minggu1cerita. Entah kebetulan atau memang sudah "direncanakan", peristiwa kecil yang gue alami hari ini dan gue ceritakan di atas seperti kembali menyadarkan gue bahwa jalan untuk bersabar itu ternyata banyak cabangnya. Dan seringkali disitulah ia hadir, berdampingan dengan sesuatu yang kita benci dan sangat tidak ingin kita jumpai. Gue jadi belajar untuk nggak egois, dan nggak memaksakan apa yang selama ini menjadi kebiasaan gue. Karena bagaimanapun, disinilah kaki gue menapak saat ini. Di tempat yang masih banyak terletak kekurangannya, yet in fact menjadi tempat yang juga memberi satu pelajaran tambahan untuk gue bisa lebih bersabar. Sebagaimana hidup yang dihiasi hilir mudik cerita manusia, bersabar ketika di perjalanan sesungguhnya bisa menjadi jalan lain untuk kita mengenal diri sendiri dan kondisi di sekitar kita.
Akhir kata, semoga sehat selalu untuk kita semua. Lebaran sebentar lagi, manteman! Sedih, nggak? Gue sih so pasti sedih banget. Banyak faktor yang membuat suasana Ramadhan tahun ini menjadi tak ada bedanya dengan tahun lalu, if you know what i mean🤧
Eniwey, ada yang pernah merasakan pengalaman buruk jugakah saat sedang di perjalanan? Coba ceritakan versimu, ya😁 Let's sharing! xx.